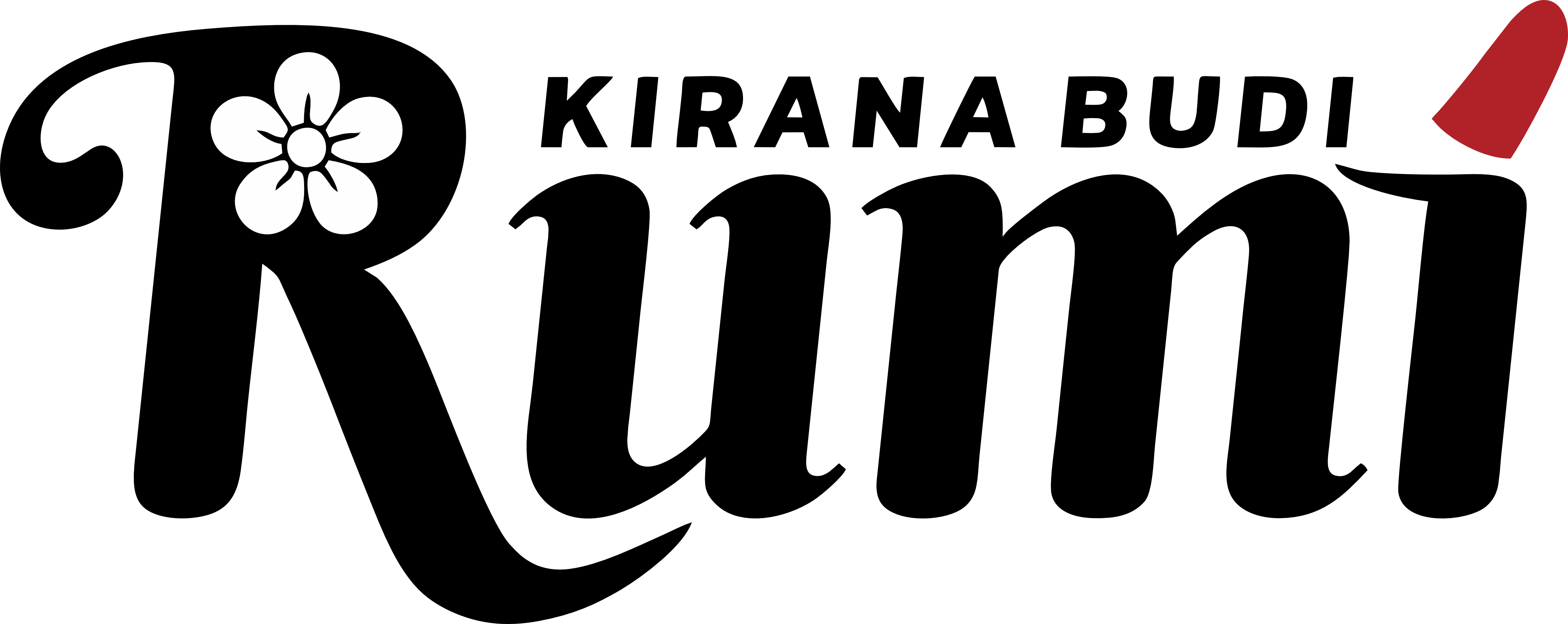Hari ini, 14 Februari 2024, seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat memiliki hak politik untuk menentukan arah bangsa lima tahun ke depan. Jika kita menelisik dinamika satu tahun ke belakang, di mana para kandidat baik calon legislatif (Caleg) maupun calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres), ataupun tim pemenang dan tim sukses yang mewakili kandidat, telah berupaya meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah kandidat terbaik untuk menjadi wakil rakyat dan pemimpin bangsa. Begitu juga respon terhadap tawaran ide atau gagasan dan janji politik dari rakyat menjadi sebuah diskursus publik dengan tensi tinggi dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini. Maka, kita akan jumpai ambiguitas dalam memahami demokrasi.
Ambiguitas demokrasi disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah rendahnya literasi politik dan minimnya kemampuan refleksi falsafah bangsa (Pancasila). Belum lagi rakyat disuguhkan dekan konten-konten media (mainstream dan media sosial) dari para kandidat dan timnya juga para praktisi hingga akademisi. Dalam masa kampanye, kita menyaksikan banyak konten, mulai dari “desak Anis, makan siang gratis, hingga tuanku adalah rakyat”. Kita juga menyaksikan protes tentang kondisi demokrasi rakyat yang diwakili oleh mahasiswa hingga guru besar, seniman hingga budayawan. Kemudian dua hari sebelum hari pemilihan kita menyaksikan film “Dirty Vote”. Semua suguhan itu patutnya dipahami dengan kemampuan daya kritis yang tinggi. Pertanyaan, apakah rakyat kita memiliki daya kritis?, silahkan di refleksi masing-masing.
Dalam memahami makna demokrasi, terkadang terdapat ambiguitas yang muncul karena demokrasi sering disamakan dengan liberalisme. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan yang mengaitkan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip liberal seperti kebebasan individu, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum yang adil. Namun, demokrasi sebenarnya mencakup lebih dari sekadar prinsip-prinsip liberalisme.
Demokrasi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, di mana “demos” berarti “rakyat” dan “kratos” berarti “kekuasaan” atau “pemerintahan”. Jadi, secara harfiah, demokrasi adalah “kekuasaan rakyat” atau “pemerintahan oleh rakyat”. Demos, yang berarti “rakyat” atau “masyarakat”, mencerminkan kolektivitas individu-individu dalam suatu entitas politik yang lebih besar. Di sisi lain, kratos, yang berarti “kekuasaan” atau “pemerintahan”, menekankan bahwa kekuasaan politik harus berasal dari dan dijalankan oleh rakyat itu sendiri.
Dalam filosofi demokrasi, hubungan antara demos dan kratos membentuk fondasi untuk sistem politik yang mengutamakan kedaulatan rakyat, representasi yang adil, serta kebebasan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Demokrasi, dalam pengertian ini, bukan hanya sebuah sistem politik, tetapi juga sebuah konsep moral yang menuntut perlakuan yang adil, partisipasi yang inklusif, dan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya.
Ambiguitas pemahaman demokrasi muncul ketika demokrasi sering dilihat secara sempit sebagai cerminan pemerintahan barat dan prinsip liberal. Hal ini terutama terjadi karena banyak negara barat, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, menganut sistem demokrasi liberal yang mencakup nilai-nilai liberalisme dalam struktur politik mereka. Dalam menghadapi demokrasi pada konteks Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi perlu diselaraskan dengan nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam Pancasila.
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mencerminkan pandangan filosofis tentang tatanan sosial dan politik yang berakar dalam keberagaman budaya dan nilai-nilai keadilan.
Pancasila, sebagai pilar filosofis negara Indonesia, mengemukakan nilai-nilai yang esensial dalam konteks demokrasi ala Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila menyiratkan makna yang mendalam untuk membentuk dasar-dasar moral dan politik yang menggambarkan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama, mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan entitas ilahi sebagai sumber moral dan spiritual bagi masyarakat Indonesia, sementara Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebagai sila kedua, menekankan perlakuan yang adil serta penghargaan terhadap martabat manusia. Kesatuan Indonesia, sebagai sila ketiga, menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman, sedangkan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, sebagai sila keempat, menyoroti partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Terakhir, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagai sila kelima, menggarisbawahi pentingnya pembangunan yang merata dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam keseluruhan, Pancasila menjadi landasan filosofis yang memperkuat esensi demokrasi Indonesia dengan meneguhkan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, partisipasi, dan persatuan dalam mencapai kemajuan bersama sebagai bangsa yang berdaulat.
Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa demokrasi dapat memiliki beragam bentuk dan aspek yang tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip liberalisme. Ini menekankan perlunya melihat demokrasi sebagai fenomena politik yang kompleks dan multidimensional, yang dapat muncul dan berkembang di berbagai konteks budaya dan politik.
Kesimpulannya, “Demokrasi Indonesia” memiliki landasan komprehensif yang tertuang dalam nilai Pancasila dan memiliki ciri khas sendiri yang tumbuh bersama nilai dan budaya masyarakat itu sendiri sebelum bangsa Indonesia berdaulat menjadi negara resmi. Mari memahami demokrasi dengan ciri kita sendiri, ciri Indonesia bukan ciri bangsa lain.
Jakarta, 14 Februari 2024
Kalaway Institute
Attar Nanny